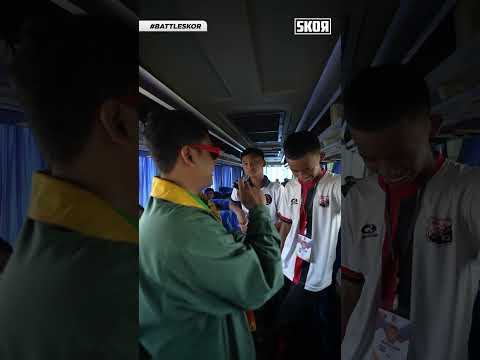SKOR.id – Enam minggu setelah San Francisco Pride, Galeri Schlomer Haus di kota itu menjadi tuan rumah What Remains, sebuah pameran karya seni yang memanfaatkan sisa-sisa dan puing-puing perayaan dua hari tersebut.
Meskipun sponsor perusahaan cenderung untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa, sampah dari pesta dan parade masih ada, begitu pula dengan masalah yang dihadapi komunitas queer — sebutan lain untuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender.
Schlomer Haus yang dibuka oleh Steffan Schlarb pada tahun 2021, berupaya memanfaatkan kembali limbah tersebut sambil menyerukan sinisme yang sering terjadi dan mengumpulkan dana untuk Queer LifeSpace, yang menyediakan layanan kesehatan mental bagi kaum queer.
Di antara karya-karya yang dipajang dan ditawarkan untuk dijual dengan 100 persen hasil disumbangkan adalah potret kolase Lil Nas X yang terbuat dari pelangi sampah, termasuk kemasan ungu untuk permen karet CBD, kotak Benadryl merah muda, sebungkus American Spirit kuning, dan kerah kulit hitam bertabur.
Schlomer Haus bekerja sama dengan sejumlah perusahaan, menguji hubungan mereka dengan komunitas queer melalui Queer Kicks, sebuah pameran yang ditampilkan dalam ComplexCon edisi tahun ini.
Saat pengunjung konvensi menghadiri konser, menikmati makanan di food court yang telah dikurasi, dan yang paling utama adalah mengejar streetwear dan sneakers edisi terbatas, koleksi karya seni yang terinspirasi dari sepatu ini berfungsi sebagai pengingat akan peran yang dimainkan oleh kaum queer dalam sebuah budaya.
Selusin seniman dipilih untuk pameran dengan menampilkan media lukisan, keramik, dan patung, dalam Queer Kicks yang hanya berlangsung dua hari pada akhir pekan lalu (18-19/11/2023) itu.
Devynn Barnes, seorang seniman wanita berkulit hitam asal Oakland, menyumbangkan Eye Believe I, sebuah ring basket di papan kayu pinus tinggi yang diukir secara melengkung dan dilukis dengan sosok yang sedang bergaya.
Jaring pada ring hitam diganti dengan rantai galvanis berwarna emas dan perak yang menjuntai ke bawah.
Barnes tumbuh besar dengan bermain bola basket. Seperti kebanyakan sneakerhead lainnya, olahraga inilah yang membuatnya jatuh cinta pada sepatu kets.
Oleh karena itu, ia mengambil pendekatan yang tidak terlalu literal untuk karya seninya, yang juga berupaya menyoroti pentingnya budaya kulit hitam dalam sepatu kets.
“Bola basket terasa sangat ekspresif dalam bentuk tubuh kita dan budaya jalanannya. Gayanya selalu menjadi sesuatu yang benar-benar membuat saya tertarik,” kata Barnes.
“Itulah tempat saya bisa bermain-main dengan ekspresi dan merasa sedikit lebih percaya diri dan berani di dalamnya. Sangat menyenangkan memiliki karya yang tak hanya mewakili perjalanan itu untuk diri saya sendiri, tetapi juga dua dunia yang tampak berbeda tetapi bagi saya selalu terasa begitu saling terkait.”
Mirip dengan apa yang dilihat di dunia olahraga, Barnes mengatakan perlakuan budaya sepatu sneaker terhadap kaum queer telah membaik namun masih ada ruang untuk perbaikan. Saat menonton Queer Kicks, ia ingin penonton menyadari bahwa ada lebih banyak hal dalam budaya ini daripada “ruang yang secara stereotip didominasi laki-laki.”
Lain lagi dengan Thomas Martinez Pilnik. Kendati tidak menyebut dirinya seorang sneakerhead, Pilnik telah terpesona dengan budaya sneaker sejak datang ke Amerika dari London, Inggris.
Kini tinggal di Los Angeles, Pilnik mendapati dirinya terjatuh ke dalam lubang pengetahuan yang dimulai dengan kursus musik Afrika Amerika di perguruan tinggi dan kemudian pindah ke New York City setelah menyelesaikan gelarnya.
Untuk Queer Kicks, Pilnik memunculkan karya yang dinamainya Running Up That Hill, sepatu terakota berlapis kaca dengan platform sepatu kets Fila favoritnya yang diberi nama sesuai dengan lagu terkenal Kate Bush.
Pilnik terlihat bermain-main dengan gagasan kenangan dan misteri bagaimana hasil pencampuran glasir, dia memercikkan keramiknya untuk memunculkan tarian “ampas malam yang sangat menyenangkan”.
“Cara saya memasuki budaya sepatu sneaker adalah dengan cara mengarungi ruang yang selama ini cukup heteronormatif dan berpotensi menjadi ruang yang bermusuhan bagi kaum queer dan perempuan,” ucap Pilnik.
“Ada sesuatu tentang platform yang secara harfiah mengangkat kami, tetapi juga membawa kami ke ruang baru. Saya merasa kuat dengan Fila ini, meskipun diberi kode sebagai sepatu wanita dan saya menemukannya di toko barang bekas. Menurut saya itu sepatu yang paling aman dan paling menyenangkan.”
Meskipun skeptis terhadap kapitalisme pelangi, Pilnik menunjuk Air Jordan 1 sebagai contoh sepatu yang memiliki kemampuan untuk mengandung “kekakuan konseptual” mengenai seberapa besar kepercayaan Nike terhadap atlet muda berkulit hitam seperti Michael Jordan.
“Ketika sebuah merek bekerja sama dengan seseorang dengan identitas yang terpinggirkan dan mendukung mereka, hal ini dapat menciptakan komunitas yang jauh lebih kuat dibanding menempelkan pelangi pada sepatu yang sudah Anda rancang,” ujarnya.
Di sisi lain, Barnes juga menyoroti hubungan artis queer Nina Chanel Abney dengan Timberland, baru-baru ini, sebagai kolaborasi yang menurutnya sangat bermakna dan ekspresif. Meski lebih memproduksi bot dibanding sneaker, namun semangat dan sejarah kolaborasi sangat berakar pada sneaker dan streetwear. Abney juga mengupas Air Jordan 2 untuk kolaborasi pada tahun 2022.
Yang pasti, Queer Kicks memberikan ruang fisik yang nyata bagi para artis untuk mengekspresikan diri dan hubungan mereka dengan sepatu kets sekaligus memberikan ruang aman bagi orang-orang queer yang hadir di ComplexCon. Namun karena ini adalah seni, masih banyak ruang interpretasi dari penontonnya.